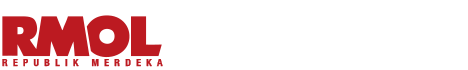- Ramai-ramai Menghajar Firli Bahuri
- Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Hak Utama Pengguna Jalan
- Jurnalisme Malas
Baca Juga
SISI teoritik hukum pidana dalam penerapan UU Tipikor dan terbukti telah berhasil dalam praktik menarik disampaikan di ruang publik untuk dijadikan pencerahan khususnya kepada penegak hukum, termasuk KPK dan juga masyarakat sebagai lembaga pengawas sosial terhadap bekerjanya pemberantasan korupsi.
Di dalam hukum pidana dikenal ucapan/pernyataan ahli hukum pidana bahwa bekerjanya hukum pidana bagai “pisau bermata dua”; satu sisi ia melindungi masyarakat dari kejahatan, tetapi di sisi lain ia “mengiris dagingnya sendiri”.
Dalam arti, memberikan penderitaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga telah menimbulkan persepsi bahwa penerapan hukum pidana telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana, apalagi kemanfaatan sosial bagi masyarakat/negara.
Secara teoritik dan doktrin hukum pidana, asas-asas hukum pidana yang diakui adalah (1) asas ultimum remedium, (2) asas tiada pidana tanpa kesalahan, 3) asas praduga tak bersalah, (3) asas hukum tidak berlaku surut (non-retroactive principles), (4) asas ne bis in idem, (5) asas lex specialis derogat legi generali, dan (6) asas in dubio pro reo.
Selain asas-asas hukum tersebut telah dikenal/diakui pula asas hukum umum, lex posteriori derogat legi priori, undang-undang yang baru (diberlakukan) mengenyampingkan undang-undang yang lama.
Begitu pula terhadap asas-asas tiada tanpa kesalahan, Romli Atmasasmita, telah memperkenalkan asas baru, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan, yang memasukkan paham utilitarianisme ke dalam teoritik hukum pidana.
Temuan asas hukum pidana baru tersebut adalah hasil penelitian atas bekerjanya hukum pidana dan bagaimana seharusnya di dalam kerangka pemikiran Pancasila sebagai satu-satunya sumber hukum di Indonesia.
Percampuran nilai Pancasila dan aliran utilitarianisme cocok untuk melengkapi asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah dipersepsi bahwa marwah hukum pidana adalah menghukum dan memberikan penderitaan semata-mata tidak ada celah hukum untuk mencapai perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana; antara pelaku, korban dan negara.
Di dalam praktik hukum pidana selama hampir 70 tahun kemerdekaan RI, terjadi ketidakpastian hukum, dan keadilan bahkan kemanfaatan hukum yang diharapkan.
Hal tersebut terjadi antara lain, asas praduga tak bersalah ditelikung asas praduga bersalah (presumption of guilt), asas ultimum remedium, telah digantikan asas primum remedium, terutama dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi (tipikor); asas tiada pidana tanpa kesalahan lebih mengutamakan lex talionis (balas dendam) dan asas lex specialis systematische specialiteit tersingkirkan oleh asas lex specialis, sanksi pidana administratif digantikan dengan sanksi pidana khusus.
Penyimpangan yang serius terjadi dalam penerapan prinsip peradilan yang jujur dan adil (fair trial) dalam penerapan Pasal 183 KUHAP yang menganut prinsip pembuktian negatif -negatief wettelijk beginsel, terutama oleh hakim/majelis hakim pengadilan sejak pada tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung.
Praktik hukum pidana yang sangat “menakutkan” dan “merusak prinsip negara hukum” terjadi ketika kekuasaan eksekutif atau legislatif disalahgunakan untuk mencampuri peradilan pidana sejak perkara di Pengadilan Negeri sampai di Peradilan Kasasi di Mahkamah Agung.
Prinsip kekuasaan yang bebas dan merdeka dari campur tangan kekuasaan telah “dihancurkan” oleh penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan finansial atau kelompok/golongan atau kepentingan politik semata-mata.
Dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan tersebut, keyakinan hakim tidak jarang tergoyahkan, hakim menjadi tidak percaya diri dan yakin lagi untuk menilai suatu perkara pidana dengan jernih dan objektif, di mana hakim bersikap masa bodoh dan menyerahkan putusan akhir pada Hakim Agung.
Praktik hukum yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tersebut telah menimbulkan penderitaan lahiriah dan batiniah pencari keadilan hanya karena ketidakmampuan secara sosial dan ekonomi.
Sedangkan kita ketahui, sebanyak 35 persen rakyat Indonesia masih berada di jurang kemiskinan sosial-ekonomi sampai saat ini.
Dalam perkara tipikor, penyebab utama dari praktik hukum pidana sebagaimana diuraikan di atas, antara lain adalah semangat penuntut, juga termasuk Majelis Hakim yang terobsesi oleh jargon “pemiskinan” para pelaku korupsi, sehingga menyirnakan sikap dan pandangan objektif, jernih, dan adil dalam menjatuhkan putusan.
Praktik hukum pidana yang telah menyimpan dan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dari tujuan kepastian hukum yang adil di atas, tidak selalu terjadi terhadap semua kasus pidana, melainkan terjadi dan mencolok pada perkara-perkara tipikor tertentu.
Perkara tipikor tertentu dimaksud yang telah diketahui umum adalah, perkara tipikor yang melibatkan anggota/pimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta pelaku usaha yang berkemampuan finansial yang memadai, dibantu oleh segelintir advokat yang tidak lagi berpijak pada status “officium nobile”.
Praktik hukum diselesaikan melalui keadilan restoratif (restorative justice) telah ditentukan, baik dengan Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung, dan Ketua MA RI merupakan upaya terbaik saat ini dari petinggi penegak hukum sebagai solusi efek samping negatif dari paham/ aliran hukum yang menyebabkan keburukan dan tidak memberikan manfaat sosial terbaik bagi pencari keadilan.
Gurubesar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Hak Utama Pengguna Jalan
- Ramai-ramai Menghajar Firli Bahuri
- Jurnalisme Malas